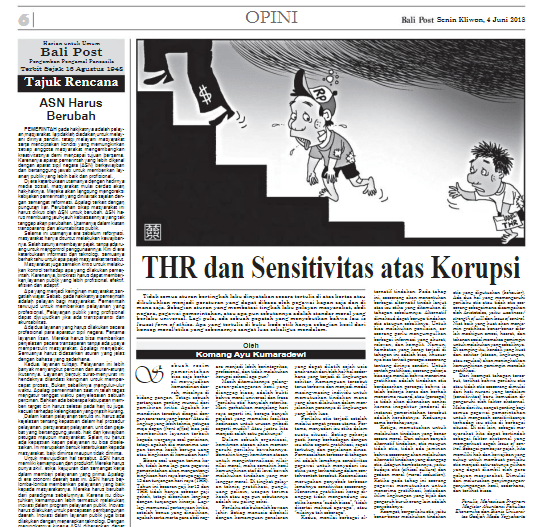*
Remy berjalan lebih cepat dari biasanya. Ia merasa diikuti. Suara langkah kaki di belakangnya terdengar ramai. Lima orang, pikirnya asal.
Beberapa meter di depan, jalanan bercabang tiga. Untuk menuju rumahnya, ia harus berjalan lurus hingga perempatan berikutnya. Namun kekhawatirannya membawa Remy berbelok ke kiri. Ada minimarket dua puluh empat jam yang bisa ia gunakan sebagai pengalih perhatian. Setidaknya ia butuh waktu untuk berpikir —tepatnya berharap— bahwa kekhawatiran ini tidak beralasan. Satu-satunya yang harus ia waspadai saat ini adalah telepon dari editornya. Remy masih punya satu minggu sebagaimana yang mereka sepakati, namun editornya bertindak seolah-olah besok adalah minggu depan itu, menuntut Remy bekerja lebih cepat.
Yusuf, petugas kasir minimarket, menyapanya. Remy membalas sekenanya. Ia menuju sembarang rak di bagian belakang toko, mencari posisi yang tepat untuk memperhatikan jalanan di depan minimarket. Ia menunggu cukup lama namun tidak ada seorang pun yang lewat. Akhirnya ia menyambar sekaleng kopi lalu menuju kasir.
“Lihat apa, sih? Kamu kelihatan khawatir.”
“Lembur?” Remy mengalihkan pembicaraan.
“Menggantikan Uti, cuma sampai tengah malam.”
Ketika membuka pintu minimarket, angin malam kembali menyapa wajah Remy. Ia melanjutkan perjalanan, berusaha melangkah dengan tenang. Di persimpangan terakhir, ia berbelok. Dari kejauhan, terlihat dua laki-laki dan satu perempuan bersandar santai pada pagar rumahnya. Remy tidak mengenal satu pun dari ketiga orang itu. Mereka bersikap seolah memiliki seluruh waktu di semesta ini.
Ketika Remy semakin dekat, laki-laki berkaus merah berjalan menyongsongnya. Wajahnya tampak lega, seolah Remy adalah orang yang selama ini ia cari dengan sungguh-sungguh dan akhirnya berhasil ditemukan.
“Remy B. Laksono?”
“Ada yang bisa saya bantu?” Suara Remy bergetar, tidak bisa ia kendalikan.
Kali ini laki-laki berkemeja putih yang berbicara, “Kami dengar kamu tinggal di sini. Maaf sudah mengganggu. Kami bisa kembali besok pagi asalkan kamu berjanji mau menemui kami.”
Remy memperhatikan mereka. Dua laki-laki tadi berbicara bergantian kepadanya. Seorang perempuan berdiri agar jauh, menunduk, dan memainkan kakinya di aspal berpasir seperti sedang menggambar sesuatu. Merasa diperhatikan, perempuan itu menjatuhkan lirikan tajam ke arah Remy. Remy merasa tak nyaman. Hanya perempuan itu, perempuan satu-satunya dalam rombongan, yang bersikap tak ramah padanya.
“Ta-tapi siapa kalian…”
Remy belum selesai bicara, mereka beranjak pergi atas komando laki-laki berkemeja putih.
“Sampai jumpa besok.” katanya.
Meski mereka datang beramai-ramai, Remy tidak merasakan adanya ancaman. Tetapi jelas kedatangan mereka bukan untuk menjalin pertemanan. Sebelum membuka kunci pagar, Remy melirik sekilas rombongan yang menjauh. Perempuan itu, yang berjalan paling belakang, mengenakan jaket berwarna hitam bertuliskan “Sekolah Khusus untuk yang Percaya – Generasi Ke-1.”
Remang bulu kuduknya melihat itu. Seingat Remy, ia belum belum pernah membicarakan soal Sekolah itu kepada siapa pun. “Ini mustahil.”
Remy mengambil gelas dan batu es dari kulkas lalu membuka kaleng kopi yang dibelinya di minimarket. Ia berjalan ragu ke arah meja kerja di sudut kamarnya. Harapannya, ingin segera menyelesaikan cerpen terakhir yang ia janjikan kepada editornya, tapi ia juga masih belum yakin dengan arah cerita yang sedang ditulis.
“Sekolah Khusus untuk yang Percaya – Generasi Ke-1. Agar setiap keputusan dilandaskan pada keyakinan bahwa alasan itu nyata, tindakan itu nyata, akibat itu nyata. Dan setiap ketidakpercayaan adalah kepercayaan itu sendiri.”
Jemarinya berhenti. Mengetukkannya ritmis di atas meja. Ia menguap satu kali. Remy berhenti di potongan tulisan yang lain. Matanya berangsur meredup. Selama ini, kopi baginya memang bukan untuk menghalau kantuk. Kopi dan air putih dapat saling menggantikan. Kapan saja.
“Ada satu ciri khas yang pasti dimiliki oleh mereka yang Percaya. Tanda lahir berbentuk daun di leher kiri.”
Alarm ponselnya berdering pukul empat pagi dan ia terbangun dalam keadaan lelah seperti habis berlari. Ia duduk tegak dan meregangkan badan sebelum beranjak ke kamar mandi. Orang bilang, keluar dari rutinitas bisa memantik kreativitas. Menulis di tempat asing mungkin ide yang bagus, pikirnya. Lima belas menit kemudian, Remy menenteng tas yang sudah lengkap dengan perlengkapan menulis. Tujuannya adalah restoran yang buka dua puluh empat jam.
Rutinitasnya memang berbeda di restoran itu, ditambah lagi ada tiga orang yang tanpa sadar berada di tempat yang tepat.
“Aku rasa Remy ketakutan. Apa kita tampak seperti penjahat?” Hiro bercermin di jendela restoran dua puluh empat jam tempat mereka menunggu pagi. Wajahnya bersih. Tak ada cambang yang ia biarkan tumbuh bahkan satu sentimeter.
“Tidak, tidak. Dia tidak ketakutan. Penulis bukan penakut. Mereka terbiasa dengan segala kemungkinan, yang terburuk sekalipun. Lagipula, hanya ini tujuan kita.” Denis menimpali sembari menunjuk amplop cokelat di atas meja. “Setelahnya, selesai. Kita menerima upah, lalu menghilang. Kita tidak pernah ada di sini.”
“Entahlah.” Monika berkata pelan. “Aku hanya ingin pulang.”
Denis dan Hiro saling menatap. Mereka bertanya pada satu sama lain di saat yang bersamaan, “Bagaimana sekarang?”
“Menunggu.” Bisik Monika.
Pukul 04.30 pagi, pintu restoran terbuka. Remy datang dengan ranselnya dan menempati kursi di dekat kasir, selisih empat meja dengan mereka. Denis dan Hiro terlihat kaget, Monika biasa saja. “Aku sudah tahu dia akan ke tempat ini. Di tidurnya, ia mengigau. Aku akan ke sana.”
Melihat Remy, Denis menyambar amplopnya lalu beranjak menuju Remy. Hiro mengikuti.
“Inspirasi datang ketika semua orang sedang terlelap, eh?” Denis membuka suara.
“Bikin kebiasaan baru?” Monika berkata ragu-ragu.
“Eh?” Remy tergagap. “Bagaimana kalian tahu kalau aku…”
“Tenang. Kami bukan orang jahat, kok.” Hiro menyela.
Denis duduk berhadapan dengan Remy, Hiro di samping Denis, dan Monika di samping Remy. Tanpa basa basi, Denis menyerahkan amplop cokelat tersebut, “Sebuah penghargaan atas kepiawaian menulis yang kamu miliki.”
“Aku tidak mau dibayar untuk menulis kebohongan.” Remy mendorong amplop yang sudah dikenalnya dengan baik kembali ke arah kedua laki-laki itu. Remy tidak menyangka isu ini belum selesai, ia sudah pernah menolak permintaan yang sama tiga tahun lalu.
“Setelah pemilihan komisaris selesai dan ia terpilih, kamu akan menerima lebih banyak. Coba bayangkan, hidup sebagai orang kaya. Asyik, bukan?” Hiro menimpali.
Remy menggeleng.
“Aku akan tinggalkan amplop ini di sini. Kamu masih punya waktu untuk berpikir. Hubungi aku kapan saja.” Denis melipat lengan kemeja putihnya lalu beranjak. Hiro pun beranjak. Monika tetap di sana.
“Mengapa kamu masih di sini? Mereka tidak menunggumu?” Tanya Remy.
“Aku ingin pulang…ke tempat yang kauciptakan. Kamu juga akan pulang ke tempat yang tepat untukmu.”
“A-aku…” Remy memandang Monika lama. Ia mengingat rumah, mengingat tawaran itu, mengingat potongan tulisannya yang terakhir. Ada tanda lahir berbentuk daun di leher kiri Monika. Ia mengabaikan Monika, segera membereskan barang-barangnya kemudian pergi dari restoran itu. Monika mengikuti. Matahari masih belum menampakkan wujudnya. Remy menggigil. Apa perempuan berjaket tipis itu tidak kedinginan, tanyanya dalam hati.
“Percaya membuatmu hangat. Kamu juga harus belajar Percaya.”
Monika melanjutkan, “Aku tahu, kok. Setiap kali jemarimu mengetik sesuatu tapi kepalamu bicara hal lain, ketika itulah kamu bicara padaku.”
“Apa ini ada hubungannya dengan tawaran kedua kaki-laki tadi?”
“Bisa iya. Bisa juga tidak. Aku tidak mengenal mereka. Aku hanya tahu bahwa mereka akan membuatmu ragu, harus ada seseorang yang membantumu membuat keputusan. Percaya.”
“Aku tidak punya tanda lahir itu. Aku bukan orang yang Percaya.” Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulut Remy.
“Siapa bilang tidak?”
Monika mengibaskan telunjuk, mendaratkannya di leher kiri Remy. Sentuhan panas sedetik mengagetkan Remy, membuatnya refleks memandang Monika dengan tatapan penuh tanya, “Apa yang kamu lakukan?”
“Aku mau pulang…ke tempat yang kamu ciptakan untukku.”
Tubuh Monika berangsur samar, berjalan cepat seolah akan menabrak Remy. Namun, alih-alih menabrak, bayangan samar itu malah memeluk. Remy memejamkan mata merasakan kehangatan yang timbul. Ketika membuka mata, ia berteman kehampaan. Matanya masih mencari-cari Monika ketika angin dingin kembali berembus menimbulkan kejang pelan di tubuh Remy. Sekilas senyum terbit di bibirnya.
“Aku pulang.”
***